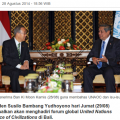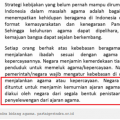Kompas.com
Malah, tak sedikit yang dibunuh dan diusir. Warga Ahmadiyah dan Syiah mengalami hal itu sampai hari ini. Kita telah membuat diskriminasi dan segregasi!
Kamis, 27 November 2014 | 14:22 WIB
Oleh: Todung Mulya Lubis
KOMPAS.com – NANI Maryani Ramli, seorang perempuan, pada 1956 memiliki surat keterangan penduduk (belum disebut kartu tanda penduduk atau KTP) untuk Daerah Kota Praja Jakarta Raya. Di sana tak tersua kolom agama.
Yang ada hanya kolom nama, jenis kelamin, bangsa (suku), umur (tanggal kelahiran), tempat kelahiran, pekerjaan, dan alamat. Sama sekali tak ada kolom agama. KTP perempuan tersebut dikeluarkan Lurah Petojo dengan stempel kelurahan.
Di Surabaya pada 1958, Soemiati mendapat kartu penduduk warga negara Indonesia yang kolom-kolomnya lebih kurang sama: tak juga memiliki kolom agama. Saat itu tiada yang mempertanyakan mengapa tidak ada kolom agama sebab agama diper- lakukan sebagai kawasan pribadi, dalam arti: merupakan urusan manusia bersangkutan. Negara tak perlu tahu agama apa yang dianut seseorang.
Konsep kewargaan
Kolom agama kala itu tak ada karena, meski dalam jagat politik Indonesia, partai-partai Islam sangat kuat (Masyumi, NU, PSII, Persis, dan lain-lain). Banyak juga partai beraliran nasionalis, sosialis, dan komunis (PNI, PSI, PKI, Murba, dan lain-lain). Apakah tidak adanya kolom agama karena kesepahaman para pemimpin negeri yang menganggap agama bukan urusan negara? Atau, tak adanya kolom agama itu dikarenakan kompromi politik antarsemua kekuatan politik?
Tak ada yang bisa menjawab pasti. Namun, kita bisa berspekulasi bahwa pada zaman yang banyak diasosiasikan sebagai zaman liberal itu, turunannya adalah bahwa konsep kewargaan lebih diutamakan. Yang terpenting apakah seseorang itu warga negara atau bukan. Seorang warga negara bebas memeluk agama atau kepercayaan atau tak beragama sama sekali. Biarlah urusan agama itu terpulang kepada manusia bersangkutan. Nyatanya, pabrik masyarakat kita tetap kukuh meski isinya kumpulan manusia dari beragam agama dan ideologi politik. Negeri ini tetap utuh. Kohesi sosial terjaga.
Kapan isu agama muncul dalam kebijakan pemerintah? Pada 1965, melalui UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, disebutkan dalam penjelasannya bahwa agama yang dipeluk penduduk di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tak salah apabila orang menafsirkan, adanya pengakuan negara terhadap agama tertentu ini dipicu juga oleh ketakutan atas bahaya komunisme yang dianggap tak beragama.
Tuduhan kudeta oleh PKI saat itu membuat mutlaknya seseorang memiliki agama jadi penting. Mereka yang tak beragama akan mudah sekali dituduh sebagai komunis dan ditangkap atau hilang. Pertanyaannya: bagaimana dengan agama lainnya, seperti Ahmadiyah, Bahai, Yahudi, dan semua aliran kepercayaan?
Di sinilah diskriminasi itu bermula. Orang Tionghoa sejak 1967 dilarang melaksanakan upacara agama mereka secara terbuka. Lebih jauh dalam KTP tak boleh ada agama Konghucu dan orang Tionghoa harus menggunakan nama Indonesia, bukan nama Tionghoa. Mereka kehilangan hak-hak sipil mereka. Bayangkan, bagaimana nasib penganut agama dan kepercayaan lainnya?
Pengukuhan keberadaan agama yang diakui negara kembali dilakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1470 Tahun 1978 yang ditegaskan Surat Edaran Mendagri No 477/1978 yang intinya hanya mengakui lima agama: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. Selanjutnya, dalam Tap MPR No II/MPR/1998 dikatakan bahwa penganut kepercayaan tak boleh mengarah pada pembentukan agama baru dan sedapat mungkin diarahkan bergabung dengan salah satu agama yang diakui negara. Tiada tempat buat agama lain dan kepercayaan.
Baru pada 2000, 35 tahun kemudian, ketika Gus Dur menjadi Presiden, keluar Keppres No 6/2000 yang mengatakan bahwa upacara keagamaan penganut Konghucu bisa dilaksanakan secara terbuka tanpa memerlukan izin. Inilah salah satu produk reformasi yang penting. Sepertinya iklim kebebasan beragama sudah mulai tumbuh dan Presiden Gus Dur yang sangat pro kemajemukan memang memberi angin segar untuk tumbuhnya masyarakat yang pluralistis.
Namun, dalam praktik, iklim masyarakat yang pluralistis itu tidak sepenuhnya mulus. Dalam kartu identitas penduduk atau KTP, misalnya, dalam kolom agama, pemilik KTP tersebut harus mencantumkan agamanya dan agama tersebut harus salah satu dari agama yang diakui. Seorang penganut agama Bahai mengeluhkan bahwa dia tak boleh mencantumkan agama Bahai di kolom agama di KTP-nya. Dia harus menulis salah satu agama yang diakui oleh negara untuk memperoleh KTP itu.
Semua ini mempunyai dampak turunan: kesulitan mengurus dan mencatatkan perkawinan, kesulitan mendapatkan akta kelahiran anak, memperoleh pekerjaan, dan sebagainya. Diskriminasi disyahkan. Akibatnya, banyak orang yang memilih tidak mempunyai KTP. Lebih jauh, dalam masyarakat mereka, yang bukan berasal dari agama yang diakui akan dituduh sebagai tak beragama atau mengikuti aliran agama sesat.
Kebebasan beragama
Meski Reformasi sudah mulai sejak 1998 dan Indonesia memiliki jaminan hak asasi yang kuat untuk menjalankan agama dan keyakinannya, baik itu atas dasar UUD 1945 maupun Kovenan Hak Sipil dan Politik, persoalan kebebasan beragama ini tak mendapat jaminan. Banyak kasus ketika penganut agama minoritas dan agama yang tak diakui negara mengalami intimidasi, teror, dan kesulitan menjalankan agama mereka. Malah, tak sedikit yang dibunuh dan diusir. Warga Ahmadiyah dan Syiah mengalami hal itu sampai hari ini. Kita telah membuat diskriminasi dan segregasi!
Ihwal kolom agama yang harus diisi dengan agama yang diakui hanya satu soal, tetapi ini soal yang sangat mengganggu dan menghambat banyak orang yang mencari pekerjaan, mendapatkan pelayanan pemerintah, dan sebagainya. UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sepertinya memberi jalan keluar dengan membolehkan kolom agama tak diisi dan mereka tetap bisa memperoleh KTP dan data mereka dicatat dalam database kependudukan.
Namun, dalam praktik, kolom agama itu dipaksakan diisi. Sedi- kit yang berani melawan. Syukur- lah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membikin gebrakan dengan mengatakan bahwa kolom agama itu tidak perlu diisi. Mendagri memulihkan kembali hak warga negara memilih agama mereka dan tak perlu mencatatkannya dalam dokumen apa pun, termasuk KTP.
Langkah Mendagri ini terbilang maju walau seyogianya Mendagri harus melangkah selangkah lagi: menghapus saja kolom agama pada KTP. Harus diakui bahwa pencantuman kolom agama ini sangat mungkin menjadi sumber diskriminasi, dan sebagai negara yang mengakui semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, merupakan kewajiban kita menghilangkan semua peluang terjadinya diskriminasi.
Seandainya secara statistik negara memerlukan data mengenai jumlah penganut setiap agama, data itu bisa diperoleh melalui berbagai survei dan sensus yang secara berkala dilaksanakan.
Perihal kolom agama ini tak perlu diperdebatkan terlalu panjang. Kebanyakan negara di dunia, termasuk negara tetangga dan negara Timur Tengah, tidak punya kolom agama dalam KTP mereka. Kebijakan tentang KTP tanpa kolom agama bukanlah sesuatu yang ahistoris.
Todung Mulya Lubis
Ketua Dewan Pendiri Imparsial