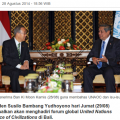Open Democracy
AHMAD SUEADY
1 December 2014
Intolerasi agama di Indonesia yang meningkat berasal dari suatu pakta politik antara mantan presiden, Bambang Yudhoyono, dan kelompok Muslim dengan tingkat toleransi rendah di negara itu. Presiden yang baru, Joko Widodo, harus menghentikan kekerasan itu sebelum terlambat. Sebuah kontribusi untuk debat openGlobalRights, Agama dan Hak Asasi Manusia.
ENGLISH
Di Indonesia, intoleransi agama oleh sebagian Muslim Sunni telah meningkat. Populasi dari negara berpenduduk 250 juta orang, sekitar 87% Muslim, dengan Muslim Sunni sekitar 99% dari populasi itu. Muslim Syi’ah sekitar 0,5% dari seluruh Muslim Indonesia, dengan Ahmadiyah sekitar 0,2%. Hingga satu dekade yang lalu, hanya ada sangat sedikit ketegangan agama antara kelompok-kelompok ini, tapi sekarang, elemen-elemen di dalam mayoritas Sunni menjadi semakin antitesis terhadap minoritas agama.
Masalah agama di Indonesia adalah bagian dari tren regional yang lebih luas. Di wilayah di dekatnya, Brunei, pemerintah telah melarang sedikitnya delapan sekolah bagus dan agama yang “menyimpang” karena mengajarkan mata pelajaran agama non-Islam. Hampir sama, Malaysia telah melarang 56 interpretasi Islam yang “menyimpang”, termasuk Ahmadiyah, Islamailiah, Syi’ah, dan Bahai. Di Myanmar, pemerintah terlibat terhadap pelarangan Muslim Rohingya karena tekanan para pemimpin agama Buddha.
Menurut akademisi Amerika Jeremy Menchik, intolerasi agama di Indonesia selama dekade terakhir berasal dari meningkatnya “nasionalisme yang saleh” yang berfokus pada “komunitas bayangan yang terikat oleh teisme umum, ortodoks dan dimobilisasikan negara.” Menchik mungkin benar, tapi nasionalisme yang saleh tidak otomatis membawa pada kekerasan. Di Malaysia, contohnya, pengadilan Syariat tingkat negara dapat memerintahkan individu yang ingin berpindah dari agama Islam, atau mereka yang menjadi pengikut kelompok terlarang, untuk masuk ke pusat rehabilitasi agama. Namun demikian, pemerintah juga melarang penggunaan kekerasan terhadap para anggota aliran kepercayaan ini, dan menghukum dengan keras para penyerang.
Mengapa intoleransi agama dan tindakan main hakim sendiri meningkat di Indonesia?
Pertama, meningkatnya kekerasan dapat dengan kuat dikaitkan dengan tindakan dari mantan Presiden Indonesia, Bambang Yudhoyono, purnawirawan jenderal yang memerintah negara ini dari tahun 2004 hingga 20 Oktober 2014.
Pada tahun 2005, Yudhoyono memulai masalah agama di negara ini dengan mendeklarasikan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah kelompok agama Sunni yang konservatif, adalah satu-satunya yang berwenang menginterpretasikan Islam, dan mengikrarkan pemerintahannya terbuka pada fatwa-fatwa mereka.
Intoleransi menjadi dilembagakan pada tingkat yang meng-khawatirkan, hak asasi manusia dari minoritas agama berada dalam ancaman, dan organisasi hak asasi manusia berjuang untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa dapat memberikan perlindungan.
MUI tidak membuang waktu. Dengan serta-merta mereka mendeklarasikan Ahmadiyah sebagai “kelompok sesat”, dan bertindak melawan “pluralisme, liberalism, dan sekularisme”. Muslim Ahmadi memercayai enam rukun iman yang sama seperti Muslim Sunni, dengan perbedaan utama yaitu bahwa pengikut Ahmadi percaya bahwa kenabian monoteistik masih berlangsung (Sunni memercayai bahwa Muhammad adalah nabi terakhir yang dikirim oleh Tuhan). Dengan secara resmi Ahmadi ditetapkan sebagai sesat, contoh-contoh pidato kebencian dan kekerasan terhadap Muslim Ahmadi meningkat dengan cepat. Intoleransi menjadi dilembagakan pada tingkat yang mengkhawatirkan, hak asasi manusia dari minoritas agama berada dalam ancaman, dan organisasi hak asasi manusia berjuang untuk melakukan pekerjaan mereka tanpa dapat memberikan perlindungan.
Kemudian, di tahun 2008, situasi memburuk ketika tiga menteri—Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, dan Jaksa Agung Hendarman Supanji—menerbitkan dekrit yang mengizinkan melarang ekspresi di depan publik secara mutlak kepada Muslim Ahmadi atas kepercayaan dan praktik agama mereka. Di tahun 2011, pemerintah Jawa Timur dan Jawa Barat (yang terakhir adalah provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia) menggunakan dekrit ini untuk langsung melarang eksistensi dan kegiatan Ahmadiyah. Sekarang, 25 dari pemerintahan daerah di negara ini melarang eksistensi kelompok sekte atau kepercayaan, dan sebagian besar pembatasan ini ditujukan kepada Ahmadiyah.
Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, militan Sunni menggunakan kekerasan terhadap Muslim Syi’ah, sebagian berdasarkan pada dekrit tahun 2012 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama di Jawa Timur yang mendeklarasikan “penghujatan” ajaran Syi’ah. Pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk menghentikan tindakan ini.
Aliansi mantan presiden Yudhoyono dengan MUI berasal dari perhitungan politik internal. Pencalonannya sebagai presiden ditolak oleh aktivis pro-demokrasi dan kelompok Muslim toleran, banyak dari mereka berkata bahwa latar belakang militer dan kurangnya rekam jejak demokrasi membuatnya tidak sesuai untuk pekerjaan ini. Yudhoyono dan sekutu politiknya lalu mendekati kelompok agama konservatif, termasuk MUI, dan meminta dukungan politik mereka. Sebagai balasan, Yudhoyono menjanjikan untuk memperlakukan doktrin MUI sebagai kebijakan.
Beberapa penasihat mantan presiden yang paling dipercaya adalah Muslim Sunni konservatif, termasuk Sudi Silalahi, diangkat sebagai sekretaris kabinet dan kemudian sekretaris negara. Silalahi dilaporkan sebagai salah satu jenderal yang mendukung militan jihad yang berangkat ke Ambon di tahun 1999 untuk menyerang ribuan Kristen Indonesia. Untuk mengatakan tidak terekam jejak pelanggaran HAM-nya sungguh meremehkan.
Diskriminasi pemerintahan Yudhoyono terhadap Ahmadiyah didorong oleh peran Ma’ruf Amin, ketua MUI, dan anggota lembaga penasihat kepresidenan (Wantimpres) bidang hubungan antar-agama. Kekuasaan Amin tumbuh dengan cepat selama kepemimpinan Yudhoyono, dan ia mampu mentransformasikan ide-ide intolerannya menjadi kebijakan negara.
Akhirnya, mantan presiden itu mengangkat tokoh Muslim konservatif untuk menjalankan kementerian agama, mengubah departemen yang dulunya toleran menjadi departemen yang curiga kepada minoritas agama non-Sunni. Juga mengangkat Gamawan fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri yang dikehatui sangat konservtaif.
Sekarang ini, banyak yang berharap bahwa presidan baru Indonesia, Joko “Jokowi” Widodo, akan membawa pemerintahan ke arah yang berbeda. Widodo, yang menurut para pemilihnya adalah politisi yang “bersih”, melakukan kampanye yang menjanjikan revolusi “mental” dengan perubahan yang menentukan dari kesewenang-wenangan dan intoleransi negara di masa lalu.
Untuk memastikan hal ini terwujud, pertama, Widodo harus menetapkan bahwa tidak seorang pun, gerakan, atau organisasi dapat menjadi satu-satunya yang berwenang menginterpretasikan agama, termasuk MUI. Berikutnya, ia harus menjamin bahwa doktrin agama tidak lagi digunakan sebagai justifikasi bagi perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Jaminan ini perlu memasukkan revisi dari UU No. 1/PNS/1965, yang dengan eksplisit melarang “interpretasi yang menyimpang” dari ajaran agama dan mandat pembubaran organisasi yang menerapkan ajaran yang menyimpang. Akhirnya, Widodo harus menunjukkan komitmen yang jelas dari pemerintahannya untuk memberikan layanan yang sama, dan menjamin kebebasan beragama, kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semua menteri dan penasihat seniornya harus dievaluasi pandangan dan rekam jejak agamanya, untuk mengeliminasi mereka yang memiliki catatan intoleransi.
Akhirnya, Widodo harus memperkuat pelaksanaan hukum, dan menghukum siapa pun yang menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri untuk alasan apa pun, termasuk alasan agama.
Jika Widodo tidak segera melakukan hal ini, Indonesia menghadapi risiko jatuh ke jalan yang berbahaya dan semakin parah.
_
About the author
Ahmad Sueady adalah Direktur Lembaga Islam Asia Tenggara (Institute of the Southeast Asian Islam) di Universitas Islam Negeri (UIN), Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia.