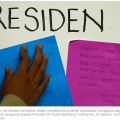Pemerintahan Wonosobo, misalnya, menangani secara khusus serta melindungi kelompok Syiah dan Ahmadiyah di wilayahnya, dimana pemerintahan kabupaten/kota lainnya seakan membiarkan diskriminasi yang terjadi terhadap kedua kelompok tersebut. Sementara pemerintahan kota Palu, melalui Walikotanya meminta maaf kepada para korban peristiwa 1965 untuk merintis upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku peristiwa 1965 di wilayahnya. Selain meminta maaf, Walikota Palu juga menangani secara khusus kepada korban peristiwa 1965 dengan mengeluarkan kebijakan kesehatan gratis bagi korban peristiwa 1965.
ELSAM
Rabu, 10 Desember 2014
Oleh: Ari Yurino
Bertepatan dengan Hari HAM Sedunia, yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Kementerian Hukum dan HAM memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/Kabupaten Peduli HAM 2014 yang digelar di Kantor Kemenkum HAM. Penghargaan Kota/Kabupaten Peduli HAM 2014 tersebut diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly kepada 55 Kota/Kabupaten yang peduli terhadap HAM di wilayahnya masing-masing.[1]
Pemberian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah dicanangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam Permenkumham tersebut ada beberapa kriteria penilaian yang ditetapkan, antara lain: 1) Hak hidup; 2) Hak mengembangkan diri; 3) Hak atas kesejahteraan; 4) Hak atas rasa aman; 5) Hak atas perempuan[2]
Sejak diberlakukannya Permenkumham tersebut, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah Kota/Kabupaten yang peduli terhadap HAM. Di tahun 2013, 19 Kota/Kabupaten memperoleh penghargaan tersebut. Sementara di tahun 2014, Kota/Kabupaten yang memperoleh penghargaan tersebut meningkat tajam menjadi 56 Kota/Kabupaten.
Data di atas menunjukkan adanya lonjakan yang tinggi dari pemerintah kota/kabupaten untuk memenuhi kriteria Permenkumham dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. “Greget pemerintah daerah sangat tinggi untuk menciptakan kota/kabupaten ramah HAM,” kata Direktur Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM Arry Ardanta Sigit dalam Konferensi Nasional Human Rights Cities di Jakarta, 9 Desember 2014.
Menurutnya penghargaan tersebut untuk memacu pemerintah Kabupaten/Kota agar mengimplementasikan beberapa hal, yaitu 1) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM); 2) Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan; 3) Three Plus Track yang mencakup Pro; Poor, Job, Growth, Justice, and Environment; serta, 4) pelaksanaan Millenium Development Goals (MGDs).
Pemerintah memang telah memiliki program nasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), yang diikuti dengan pembentukan panitia RANHAM hingga tingkat kabupaten/kota. RANHAM menjadi semacam pedoman bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Namun evaluasi dari masyarakat sipil menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaannya. Dari 103 program RANHAM 2004-2009, hanya 56 program saja yang berjalan. Lainnya terhambat karena kurangnya dorongan politik mulai dari birokrasi lintas departemen sampai dengan pemerintah daerah, minimnya kecakapan panitia RANHAM di daerah, hingga perencanaan yang tidak disertai dengan penganggaran[3]. Hal yang sama juga terjadi pada RANHAM 2011-2014 yang dirasa masih banyak kelemahan substansial dan lemahnya pemahaman panitia RANHAM mengenai program RANHAM.[4]
Sementara terkait penilaian kabupaten/kota yang peduli HAM menurut pemerintah juga dinilai bermasalah. Pasalnya, beberapa kota/kabupaten yang dianggap peduli HAM ternyata sangat bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Misalnya saja kasus-kasus diskriminasi yang masih terjadi di wilayah Jawa Timur, sementara ada 7 kabupaten/kota yang menerima penghargaan dari pemerintah sebagai kabupaten/kota peduli HAM di tahun 2014[5].
Dalam Konferensi Nasional Human Rights Cities yang digagas INFID dan didukung oleh ELSAM, pemerintah kabupaten Wonosobo, Save the Children, British Embassy dan ICCO pada 9 Desember lalu berhasil mengungkap inovasi yang baik serta kepemimpinan lokal yang cukup menonjol dari berbagai daerah. Sekitar 10 kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia mempresentasikan inovasi-inovasi yang telah dan sedang dijalankan oleh masing-masing kepala daerah tersebut. Kebanyakan kepala daerah itu mengungkapkan perubahan “wajah” kota/kabupaten di wilayah kekuasaannya, mulai dari pembangunan taman, saluran air, atau tempat wisata baru. Hal ini tentunya belum cukup untuk menyebut berbagai kota tersebut sebagai kota/kabupaten ramah HAM.
Kesempatan untuk mendorong kota/kabupaten menjadi ramah terhadap HAM menjadi sangat terbuka peluangnya setelah lahirnya Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999, sebagai awal mulanya era desentralisasi di Indonesia. Perimbangan kekuasaan pun perlahan-lahan beralih ke daerah-daerah (kota/kabupaten), mulai dari mengatur pemerintahan hingga pemilihan kepala daerah. Pembangunan di daerah tersebut, khususnya di kota, tentunya memunculkan perpindahan penduduk yang besar dari desa ke kota. Data WHO menunjukkan adanya perpindahan penduduk yang signifikan ke kota. Tahun 1990, warga dunia yang tinggal di perkotaan kurang dari 40%, sementara tahun 2010, kurang lebih 50% populasi di dunia hidup di perkotaan. WHO bahkan memprediksi pada tahun 2030, 6 dari 10 orang di dunia akan tinggal di kota[6]. Para ahli juga memperkirakan pada tahun 2050 tingkat urbanisasi di dunia mencapai 65%[7]. Sementara di Indonesia, data Bank Dunia menunjukkan hampir setengah dari 245 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah perkotaan dan kebutuhan akan layanan pengelolaan air limbah yang aman bertumbuh dengan cepat[8].
Tingginya angka urbanisasi yang diprediksi oleh lembaga internasional dan para ahli tersebut disebabkan salah satunya karena model pembangunan yang diterapkan di sebagian besar negara-negara miskin. Model pembangunan tersebut ditandai dengan kecenderungan untuk melakukan konsentrasi pada pendapatan dan kekuasaan sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pengucilan, yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan, mempercepat proses migrasi dan urbanisasi, segregasi sosial dan spasial serta privatisasi kesejahteraan umum maupun ruang publik. Di Indonesia sendiri, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin dari tahun 1970-2003 masih didominasi oleh pedesaan[9]. Tingginya kemiskinan di pedesaan inilah yang diduga menjadi penyebab utama perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Namun ketika migrasi terjadi dari desa ke kota, hal ini belum tentu memperbaiki kondisi dan kualitas masyarakat yang bermigrasi. Hal ini dapat dilihat dari data BPS sebelumnya yang menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di perkotaan juga tidak berbeda jauh dengan di pedesaan. Menurut mahasiswa Ilmu Politik City University of New York dan Pemimpin Redaksi IndoprogressCoen Husain Pontoh, kemiskinan di perkotaan lebih disebabkan karena kapasitas ruang di perkotaan sangat terbatas untuk menampung jumlah penduduknya. Sementara model pembangunan yang diterapkan di perkotaan lebih untuk melayani kebutuhan segelintir penduduk menengah ke atas[10]. Sebagai contoh, hal ini dapat kita lihat dari menjamurnya pembangunan pusat perbelanjaan (mall) dan apartemen sebagai tempat tinggal untuk kelas menengah ke atas. Pada tahun 2013, di Jakarta sudah berdiri 173 unit mall yang memakan lahan seluas 3.920.618 meter persegi[11]. Sementara pertumbuhan apartemen pada tahun 2013 mencapai rekor tertinggi, yakni 117.276 unit apartemen baru. Pertumbuhan apartemen ini mencapai 20,2 persen lebih tinggi ketimbang 2011 yang mencapai 18,97 persen[12].
Meningkatnya kehadiran bangunan privat dibandingkan bangunan publik, menurut dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia Irwansyah dimungkinkan oleh adanya serangkaian kebijakan dan relasi yang menyertai serta yang mengoptimalkan logika mekanisme pasar dalam praktek pengembangan dan pengelolaan ruang kota[13].
Konsekuensi dari banyaknya model pembangunan yang berorientasi privat tersebut adalah penggusuran terhadap warga miskin di perkotaan. Di Jakarta, misalnya, penggusuran terhadap warga miskin untuk pembangunan bangunan privat seperti mall dan apartemen kerap kali dilakukan[14]. Hal ini, menurut David Harvey, merupakan konsekuensi atas gerak internal kapitalisme yang harus selalu menguasai ruang sebagai sarana untuk ekstraksi nilai lebih[15]. Pada momen itulah, kapitalisme selalu akan berusaha untuk menghilangkan ruang-ruang yang tidak menguntungkan bagi dirinya.
Dalam wawancara bersama Coen Husain Pontoh[16], ia juga menyebutkan model pembangunan di perkotaan untuk melayani kelas menengah ke atas tersebut tidak nyambungdengan kebutuhan mayoritas penduduk kota yang miskin, sehingga lahir daerah-daerah kumuh, perumahan tak layak tinggal, sarana air bersih yang sangat terbatas, tingkat kriminalitas yang tinggi, pengangguran, pengemis, anak jalanan yang membludak, kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak berkualitas dan sebagainya.
Untuk mengubah wajah kota menjadi ramah HAM atau mementingkan kepentingan warga kotanya maka mutlak diperlukan keterlibatan warga kota. Selama ini warga kota disingkirkan keterlibatannya dari proses perencanaan dan pembangunan perkotaan. Tanpa pelibatan masyarakat yang luas, maka sebaik apapun pemerintahan kota yang terpilih, maka ia akan terjebak pada pola pembangunan kota sebelumnya, yang hanya melibatkan para teknokrat yang memiliki keahlian khusus. Walaupun beberapa kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah dirasa cukup baik, namun keterlibatan warga kota untuk membangun kotanya mutlak diperlukan. Hal inilah yang Hak warga atas Kota.
Terminologi hak atas kota ini untuk pertama kalinya dikemukakan oleh sosiolog-cum filsuf Prancis Henri Lefebvre pada tahun 1968. Menurutnya hak terhadap kota merupakan sesuatu yang nyata, yang hadir dengan segala kerumitannya saat ini untuk kemudian mentransformasikan dan memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik kekinian[17]. Dengan pengertian ini, menurut Coen Husain Pontoh, warga miskin tidak hanya berhak untuk mengakses pendidikan dan kesehatan gratis, tetapi warga miskin yang menetap di kota juga aktif terlibat dalam proses perubahan itu.
Dalam konferensi nasional Human Rights Cities yang bertajuk “Membangun Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia,” pada 9 Desember lalu, hal senada juga diungkapkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurutnya pelibatan masyarakat atau komunitas dalam merumuskan kebijakan di tingkat kota/kabupaten menjadi keharusan pada saat ini. Untuk itu, katanya, birokrat pemerintahan harus bisa melayani dan mudah disentuh oleh masyarakatnya, baik secara tatap muka maupun menggunakan teknologi informasi.
“Di waktu senggang, saya bermain twitter untuk mengontrol apa yang terjadi,” katanya dalam pembukaan konferensi nasional tersebut.
Marco Kusumawijaya dari Rujak Center for Urban Studies (RCUS) yang menjadi salah satu pembicara dalam sesi pleno di konferensi nasional tersebut menambahkan sebagai kota/kabupaten ramah HAM, kebijakan publik harus bisa diakses oleh masyarakat. “Kota mempunyai daya dukung yang dinamis, sehingga masyarakat harus terlibat,” ujarnya.
Selain partisipasi warga kota sebagai salah satu indikator kota/kabupaten ramah HAM, Shin Gyonggu dari Gwanju International Center juga mengungkapkan pentingnya pendidikan HAM juga bagi warga kota juga menjadi penting bagi pengembangan HAM di kota. Shin Gyonggu yang mempresentasikan kota Gwanju sebagai salah satu kota rujukan yang ramah HAM menjelaskan bahwa pembangunan memorialisasi dan pemenuhan hak atas pemulihan juga menjadi penting.
Pemaparan inovasi yang dilakukan kepala daerah yang diundang dalam konferensi nasional Human Rights Cities memang beragam. Namun yang menarik perhatian adalah inovasi yang dilakukan oleh Bupati Wonosobo dan Walikota Palu. Kedua kepala daerah ini bukan hanya memaparkan pembangunan yang dilakukan mereka di daerahnya masing-masing. Namun mereka juga memaparkan tindakan pemerintahan di kedua daerah tersebut dalam melakukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
Pemerintahan Wonosobo, misalnya, menangani secara khusus serta melindungi kelompok Syiah dan Ahmadiyah di wilayahnya, dimana pemerintahan kabupaten/kota lainnya seakan membiarkan diskriminasi yang terjadi terhadap kedua kelompok tersebut. Sementara pemerintahan kota Palu, melalui Walikotanya meminta maaf kepada para korban peristiwa 1965 untuk merintis upaya rekonsiliasi antara korban dan pelaku peristiwa 1965 di wilayahnya. Selain meminta maaf, Walikota Palu juga menangani secara khusus kepada korban peristiwa 1965 dengan mengeluarkan kebijakan kesehatan gratis bagi korban peristiwa 1965. Hal ini tentunya lebih maju jika dibandingkan pemerintah pusat, yang hingga saat ini masih belum mengakui korban peristiwa 1965.
Apa yang dilakukan oleh kedua kepala daerah tersebut dapat kita sebut sebagai permulaan kota ramah HAM. Prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi titik tolak dari apa yang dilakukan oleh kedua kepala daerah tersebut. Untuk itu, seharusnya pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM, dapat mendorong penitikberatan penilaian untuk kota peduli HAM sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sejak tahun 2013 pemerintah memberikan penghargaan terhadap sejumlah kota/kabupaten yang peduli terhadap HAM. Namun sayangnya, kriteria dan indikator penilaian untuk kota/kabupaten peduli HAM masih belum mencakup prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, sehingga masih banyak kritik dari masyarakat daerah tersebut, ketika suatu kota/kabupaten menerima penghargaan kota/kabupaten peduli HAM dari pemerintah. Untuk itu, revisi kriteria dan indikator pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, mengenai kota/kabupaten peduli HAM menjadi sangat penting untuk dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.
Charlotte Mathivet menjelaskan hak atas kota mencakup dimensi dan komponen-komponen sebagai berikut:[18] 1) hak terhadap habitat yang memfasilitasi sebuah jaringan kerja hubungan sosial; 2) hak terhadap kohesi sosial dan pembangunan kolektif dari kota; 3) hak untuk hidup secara bermartabat; 4) hak untuk bisa hidup berdampingan; 5) hak untuk mempengaruhi dan mendapatkan akses terhadap pemerintah kota; dan, 6) hak untuk diperlakukan secara sama.
Masih menurut Mathivet, hak atas kota atau kota/kabupaten ramah HAM tersebut dapat dicapai jika warga kotanya dijamin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) melakukan aktivitas secara penuh sebagai warga negara; 2) mendapatkan perlakukan yang sama tanpa diskriminasi; 3) perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok dan rakyat yang menghadapi situasi-situasi yang rentan; 4) adanya komitmen sosial dari sektor-sektor swasta; 5) adanya rangsangan bagi solidaritas ekonomi dan kebijakan pajak progresif; 6) manajemen dan perencanaan sosial atas kota; 7) produksi sosial di lingkungannya; 8) pembangunan perkotaan yang setara dan berkelanjutan; 9) hak atas informasi publik; 10) hak atas kebebasan dan integritas; 11) hak atas keadilan; 12) hak atas keamanan dan kedamaian publik, demi kehidupan bersama yang multikultur dan saling mendukung; 13) hak terhadap air, akses dan ketersediaan atas pelayanan publik dan domestik; 14) hak atas transportasi publik dan mobilitas perkotaan; 15) hak atas perumahan; 16) hak atas kerja; dan, 17) hak atas lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.
Persoalan yang lain adalah banyak kepala daerah merasa telah memenuhi hak asasi warga kotanya ketika telah merubah “wajah” kota/kabupaten menjadi lebih indah. Hal ini terungkap dari presentasi yang dipaparkan oleh sejumlah kepala daerah yang diundang dalam konferensi nasional Human Rights Cities di Jakarta pada 9 Desember lalu. Jelas kriteria tersebut belum cukup untuk menyebut kota/kabupaten ramah HAM. Pertanyaan penting yang diajukan oleh dosen pasca sarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Budi Widianarko dalam sesi diskusi di konferensi nasional Human Rights Cities adalah apakah perubahan “wajah” kota/kabupaten dari kumuh menjadi indah tersebut dapat dinikmati oleh seluruh warga kota? Hal ini menjadi penting karena beberapa kepala daerah mengungkapkan bahwa mereka mengubah “wajah” kota/kabupaten dari wilayah yang kumuh menjadi tempat-tempat wisata. Apakah tempat wisata tersebut dapat diakses oleh seluruh warga kotanya, atau bahkan apakah ada warga kota yang dikorbankan dari perubahan “wajah” kota tersebut?
Hal ini juga dinyatakan oleh Wardah Hafidz dari Urban Poor Consortium (UPC) yang menegaskan bahwa salah satu prinsip kota ramah HAM adalah kota yang tidak ada penggusuran paksa. Menurutnya, pelibatan masyarakat menjadi penting dalam merumuskan tata kota. “Tata kota harus disusun dari bawah, dari tingkat RT/RW,” ujarnya.
Paradigma mengenai prinsip-prinsip HAM artinya juga harus dimiliki oleh seluruh kepala daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Sederhananya, kota/kabupaten ramah HAM bukan hanya merubah “wajah” kota menjadi lebih indah melalui pembangunan infrastruktur, namun kepala daerah tersebut juga harus menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga kotanya. Peluang ini terbuka lebar bagi seluruh kepala daerah di Indonesia mengingat era desentralisasi telah dilaksanakan sejak tahun 1999. Melalui kebijakan desentralisasi tersebut, kekuasaan pemerintah daerah menjadi lebih luas, khususnya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi warga kotanya.
Perubahan paradigma dari kepala daerah mengenai prinsip-prinsip HAM dalam mengelola kota/kabupatennya tentunya tidak semudah membalikkan tangan. Untuk itu, dibutuhkan pendidikan mengenai HAM bagi kepala daerah, bahkan bisa diperluas bagi seluruh perangkat pemerintahan daerah yang berkepentingan, untuk memahami HAM agar dalam mengelola kota/kabupatennya dapat sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan pendidikan HAM yang terus menerus dan berkelanjutan bagi perangkat pemerintahan daerah di Indonesia, maka mewujudkan kota/kabupaten yang ramah HAM bukanlah sesuatu yang mustahil.
Selain perubahan atau revisi kriteria penilaian dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai kota/kabupaten peduli HAM dan perubahan paradigma dari kepala daerah mengenai kota/kabupaten yang ramah HAM, yang lebih penting adalah mengenai pelibatan masyarakat atau warga kota dalam merumuskan kebijakan kotanya. Beberapa pengalaman kota-kota di belahan dunia lain telah mempraktekkan pelibatan warga kota dalam merumuskan kebijakan kotanya, seperti Gwangju, Porto Alegre atau pembangunan Dewan Komunal di Venezuela. Di Gwangju, partisipasi warga kota yang dimulai di Gwangju pada tahun 2001, akhirnya dijadikan model pelibatan masyarakat di Korea Selatan pada tahun 2014. Sementara anggaran partisipatoris diterapkan di Porto Alegre, Brazil pada tahun 1989. Melalui sistem ini, warga kota berpartisipasi dalam menentukan alokasi anggaran kota untuk kebutuhan warga kota. Sedangkan platform Dewan Komunal di Venezuela, yang diperkenalkan oleh mantan presiden Hugo Chavez, menjadi salah satu tulang punggung berjalannya pemerintahan di sana.
Pengalaman-pengalaman beberapa kota di belahan dunia tersebut menarik jika menjadi pembelajaran bagi kepala daerah untuk mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Pengalaman dan keberhasilan beberapa kota tersebut tentunya dapat dijadikan acuan bagi pemerintahan kota/kabupaten di Indonesia dalam mewujudkan kota/kabupaten ramah HAM. Bahkan, dari berbagai pengalaman kota-kota di dunia tersebut, maka bukan tidak mungkin kepala daerah dan perangkat pemerintahan daerahnya merumuskan sendiri kebijakan-kebijakan yang ramah HAM sesuai dengan kebutuhan warga kotanya dan geografis wilayahnya.
[1] “Menteri Hukum Berikan Penghargaan Kota/Kabupaten Peduli HAM 2014,” detik.com, 11 Desember 2014, http://news.detik.com/read/2014/12/11/002512/2773923/10/1/menteri-hukum-berikan-penghargaan-kota-kabupaten-peduli-ham-2014(diakses 24 Desember 2014)
[2] Dalam lampiran Permenkumham No 25 Tahun 2013 dijelaskan indikator penilaian terhadap hak hidup mencakup 1) angka kematian ibu; angka kematian bayi; dan, 3) tutupan vegetasi pada kawasan berfungsi lindung. Indikator untuk hak mengembangkan diri mencakup: 1) persentase anak usia 7-12 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SD; 2) persentase anak usia 13-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan tingkat SMP; 3) persentase anak berkebutuhan khusus yang memperoleh pendidikan; dan, 4) persentase penyandang buta aksara. Indikator Hak atas Kesejahteraan mencakup: 1) penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk; 2) persentase keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah; 3) persentase rumah tidak layak huni; 4) persentase angka pengangguran; 5) persentase penurunan jumlah anak jalanan dari tahun sebelumnya ke tahun berjalan; 6) persentase balita kurang gizi; dan, 7) persentase keluarga yang belum memiliki akses terhadap jaringan listrik. Indikator hak atas Rasa Aman mencakup jumlah demonstrasi yang anarkis. Sedangkan indikator Hak Perempuan mencakup: 1) persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan daerah; dan, 2) persentase kekerasan terhadap perempuan.
[3]“Pemerintah Siapkan RANHAM Periode 2010-2014,” hukumonline.com, 4 Februari 2010,http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6aa27ae0e2f/ranham(Diakses 24 Desember 2014)
[4] Lihat Task Force Pemantauan RANHAM, Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Protocol to the Convention against Torture (CAT) dalam RANHAM 2004-2009 dan Perencanaan RANHAM 2010-2014 (Jakarta, The Partnership for Governance Reform, Juni 2012),http://www.kemitraan.or.id/sites/default/files/20120809092409.Evaluasi%20Pelaksanaan%20RANHAM%202004-2009.pdf(Diakses 24 Desember 2014). Lihat juga Matriks Perpres Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011-2014,http://www.ohchr.org/Documents/Issues/NHRA/NAPIndonesiaTahun2011_2014.pdf
[5] “Pemprov Dinilai Tak Serius Tangani Kasus HAM,” Koran Sindo, 11 Desember 2014,http://www.koran-sindo.com/read/935796/151/pemprov-dinilai-tak-serius-tangani-kasus-ham(Diakses 24 Desember 2014)
[6] INFID, Booklet Konferensi Nasional Human Rights Cities, 2014, hlm 6,http://infid.org/pdfdo/1418192699.pdf
[7] Lihat Piagam Dunia Hak Atas Kota
[8] INFID, Loc.Cit., hlm 7
[9] Lihat data BPS mengenai Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, 1970-2003. Penduduk miskin di pedesaan sekitar 14,42%, sementara penduduk miskin di perkotaan sekitar 8,52% di September 2013, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=7
[10] Coen Husain Pontoh, wawancara dengan Rusman Nurjaman, Harian Indoprogress, 18 Februari 2003, http://indoprogress.com/2013/02/coen-husain-pontoh-partisipasi-warga-kunci-pembangunan-kota/(Diakses 24 Desember 2014)
[11] “Data Pertumbuhan Mal di Kawasan Jakarta,” tempo.co,18 September 2013,http://www.tempo.co/read/news/2013/09/18/083514312/Data-Pertumbuhan-Mal-di-Kawasan-Jakarta(Diakses 24 Desember 2014)
[12]“Apartemen Makin Menjamur di Jakarta,” tempo.co,8 Januari 2013,http://www.tempo.co/read/news/2013/01/08/093452994/Apartemen-Makin-Menjamur-Di-Jakarta/(Diakses 24 Desember 2014)
[13] “Irwansyah: Wargalah Yang Sehari-hari Membentuk Kota,” wawancara dengan Fathimah Fildzah Izzati, Left Book Review, 17 Desember 2013,http://indoprogress.com/2013/12/irwansyah-wargalah-yang-sehari-hari-membentuk-kota/(Diakses 24 Desember 2014)
[14] “Hak atas Kota: Hak untuk Bermukim di Pusat Kota!” 13 Juni 2013,http://rujak.org/tag/penggusuran/(Diakses 24 Desember 2014)
[15] David Harvey, “Social Justice and The City” (New York: Routledge, 1973) seperti dikutip dalam Rio Apinino, “Penyingkiran Kaum Miskin Kota dan Hak Atas Kota,” Harian Indoprogress, 20 Agustus 2014, http://indoprogress.com/2014/08/penyingkiran-kaum-miskin-kota-dan-hak-atas-kota/(Diakses 24 Desember 2014)
[16] Coen Husain Pontoh, Loc Cit., 18 Februari 2013
[17] “Hak Atas Kota,” Harian Indoprogress, 25 Januari 2013,http://indoprogress.com/2013/01/hak-atas-kota-2/(Diakses 24 Desember 2014)
[18]City for All: Proposals and Experiences towards the RIght to the City, eds. Ana Sugranyes., Charlotte Mathivet (Santiago: Habitat International Coalition, 2010) seperti dikutip oleh Coen Husain Pontoh., Ibid